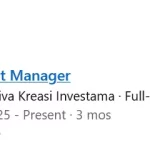Tentang Iri Hati pada Mereka yang Punya Cita-Cita, dan Perjalanan Menerima Diri Sendiri.
Setiap kali saya mendengar seseorang berbicara dengan penuh gairah tentang “cita-cita” mereka, ada sebagian kecil dari diri saya yang merasa kagum. Keren yah, pikir saya. Keren yah orang yang punya cita-cita.
Keren, karena saya tidak seperti itu.
Sejak lama, saya bergulat dengan label yang saya sematkan pada diri saya sendiri: “manusia tanpa ambisi.”
Polisi, Dokter, dan Saya yang Kosong
Tentu, saya pernah memilikinya. Waktu kecil, saya ingin sekali menjadi polisi. Saya ingat ibu saya membelikan baju seperti tentara dan polisi. Di mata saya, mereka terlihat keren, gagah, dan—yang saya yakini saat itu—sebagai pembela kebenaran.
Tapi ambisi itu sepertinya memiliki tanggal kadaluarsa.
Saat saya masuk SD, cita-cita itu pudar begitu saja. Lenyap tanpa jejak. Di saat teman-teman saya masih dengan mantap menjawab “dokter” atau “insinyur”, saya hanya diam. Bukan karena saya punya rahasia, tapi karena di dalam kepala saya benar-benar kosong. Saya tidak berkeinginan menjadi apa-apa.
Kekosongan itu kemudian saya isi dengan “mencoba-coba”.
Babak ‘Jack of All Trades’: Mencari Sesuatu yang ‘Klik’
Saya tidak punya dorongan internal yang kuat, jadi saya mengikuti arus eksternal.
Saya belajar basket karena kakak saya adalah tim basket di sekolahnya. Saya lanjut bermain sampai SMA. Hasilnya? Saya ga jago. Saya berhenti.
Saya belajar gitar, mungkin karena dulu saya suka bermain ukulele. Nadanya asyik, kelihatannya seru. Tapi itu tidak bertahan lama. Saya berhenti dan tidak pernah benar-benar menekuninya lagi.
Saya melihat kakak-kakak saya yang orang multimedia. Mereka bisa menggambar dan membuat desain yang keren. Saya coba ikuti. Hasilnya? Bisa ditebak, saya ga jago.
Setiap kali saya memulai sesuatu, saya seperti menabrak dinding “cukup tahu”. Saya tidak pernah memiliki daya juang untuk menjadi “master” di bidang itu. Saya hanya seorang Jack of all trades—bisa sedikit-sedikit, tapi tidak ada yang benar-benar dikuasai.
Pilihan Logis dan Realitas yang Menampar
Pola ini berlanjut hingga saya memilih jurusan kuliah.
Saya masuk IT (Teknik Informatika). Mengapa? Bukan karena passion menggebu-gebu. Alasan saya sederhana saja: saya pikir prospek kerjanya bagus, dan kelihatannya keren saja bisa ngoding seperti di film-film peretas.
Lalu, realitas menampar saya.
Ternyata, saya ga bisa ngoding. Ga jago. Saya bisa memahaminya di permukaan, tapi saya tidak pernah bisa “klik” seperti teman-teman saya yang bisa tenggelam berjam-jam untuk ngoding.
Di titik inilah perasaan “tanpa ambisi” itu mencapai puncaknya. Saya merasa seperti produk gagal. Saya iri pada mereka yang punya satu hal yang mereka cintai dan tekuni. Saya iri pada si spesialis. Saya, si generalis, merasa seperti seorang penipu yang hanya tahu kulitnya saja.
Kekuatan Tersembunyi Si ‘Master of None’
Butuh waktu lama bagi saya untuk sadar, bahwa mungkin cara pandang saya—dan kita semua—tentang ‘ambisi’ itulah yang keliru.
Kita terlanjur menyamakan “ambisi” dengan “spesialisasi”. Kita begitu memuji seorang spesialis yang mendedikasikan 10.000 jam untuk menguasai satu hal. Tapi di saat yang sama, kita meremehkan seorang generalis—orang seperti saya—yang menggunakan 10.000 jam yang sama untuk mempelajari 10 hal berbeda.
Benarkah orang seperti saya ini tidak punya ambisi?
Saya mulai berani menjawab: Tidak.
Ambisi saya mungkin bukan ambisi untuk status atau pangkat. Ambisi saya adalah keingintahuan (curiosity). Ambisi saya adalah untuk tumbuh. Bukan hanya tumbuh ke atas menjadi gunung yang tertinggi, tapi tumbuh ke samping, ke segala arah, menjadi ekosistem yang paling kaya—lengkap dengan danau, hutan, dan lembahnya.
Saya juga baru teringat lanjutan dari peribahasa lama itu: “A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one.” (Seorang generalis mungkin tidak menguasai satu hal, tapi seringkali ia lebih baik daripada seorang master di satu hal).
Di dunia yang berubah secepat kilat ini, si spesialis bisa sangat rapuh. Ketika keahlian tunggalnya tidak lagi relevan, ia goyah.
Namun, si Jack of all trades? Dia adalah definisi dari adaptasi. Dia adalah bunglon. Dia mungkin tidak bisa menyelam sedalam spesialis, tapi dia bisa terbang, memanjat, dan berenang di berbagai kolam.
Kekuatan terbesarnya, yang dulu tidak saya sadari, adalah kemampuannya menyambungkan titik-titik (connecting the dots). Dia bisa melihat pola yang tidak dilihat orang lain. Dia bisa mengambil konsep dari satu bidang (pengalaman saya di desain, misalnya) dan menerapkannya untuk memecahkan masalah di bidang lain (manajemen).
Saya bukan “master of none”. Saya adalah “master of learning” dan “master of context”.
Pencerahan: Peran Seorang Project Manager
Dan kini, lucunya, saya bekerja sebagai seorang Project Manager.
Sebuah peran yang membuktikan semua teori itu. Peran yang ironis. Seorang PM tidak dituntut untuk menjadi coder terhebat di tim. Seorang PM tidak harus menjadi desainer paling artistik. Seorang PM tidak harus menjadi analis paling tajam.
Seorang PM dituntut untuk memahami bahasa mereka semua.
Peran ini menuntut saya untuk menyambungkan titik-titik.
Ternyata, pengalaman saya yang “ga jago” coding itu sangat berharga. Itu membuat saya bisa berempati dengan kesulitan tim. Pengalaman saya yang “ga jago” desain membuat saya bisa menghargai proses. Bahkan pengalaman “ga jago” main basket mengajarkan saya tentang dinamika tim.
Saya akhirnya sadar. Saya tidak “tanpa ambisi”.
Ambisi saya bukanlah sebuah jabatan atau keahlian tunggal. Ambisi saya adalah keingintahuan. Ambisi saya adalah menjadi jembatan.Menjadi seorang Jack of all trades ternyata bukanlah kegagalan. Itu adalah sebuah proses latihan yang panjang untuk peran saya hari ini. Saya tidak perlu menjadi “master of one”. Saya hanya perlu menjadi “master of connecting” mereka semua